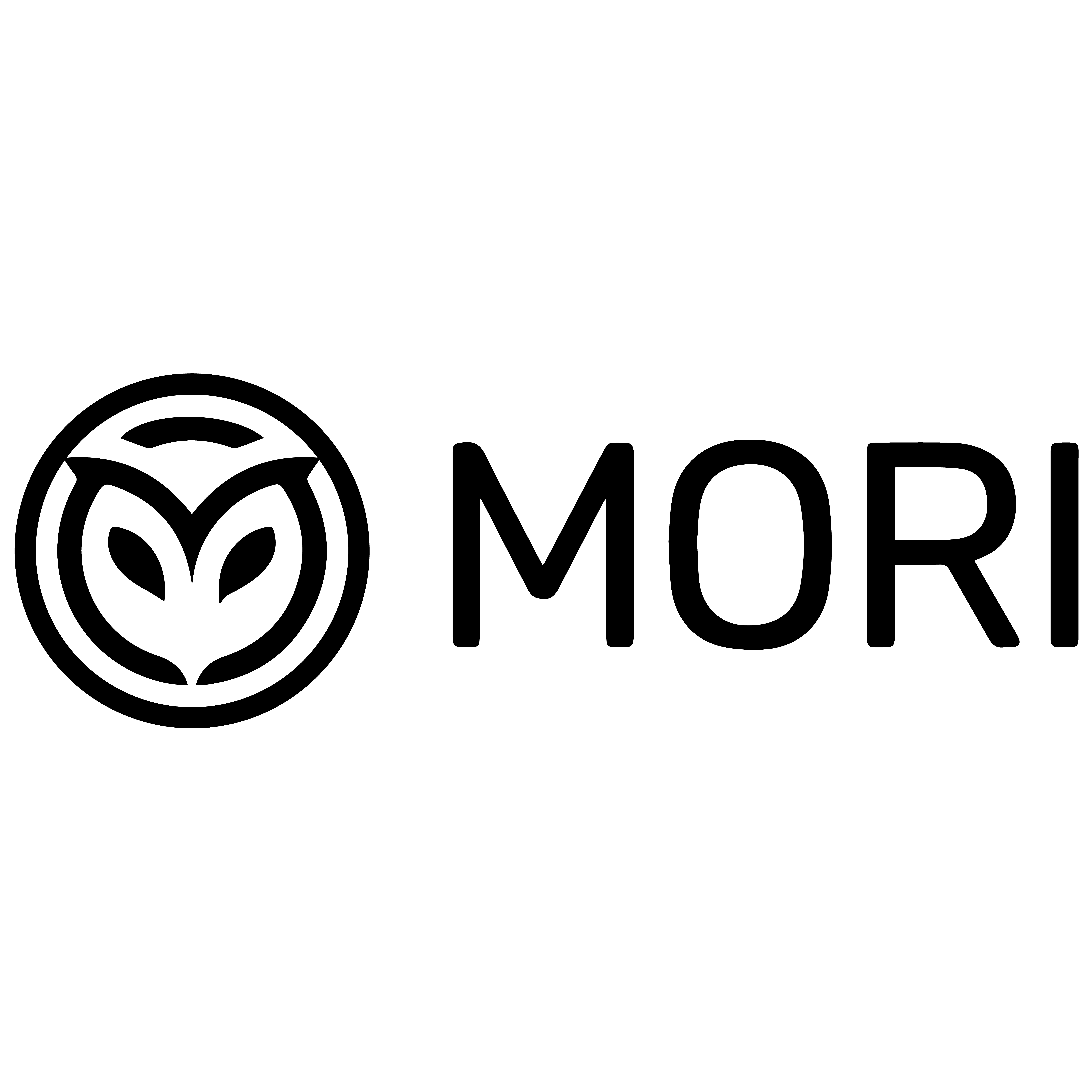Oleh R.H. Authonul Muther
Di siang terik di Kota Paris, dalam perjalanannya menuju Vincennes-Saint-Denis, lelaki yang kini berumur tiga puluh delapan tahun itu melintas di kawasan Gereja Basilika Sacré Cœur. Tepat di hadapan Gereja Kuno Basilika yang gotik dan bersejarah, lelaki rendah hati dan penuh keugaharian itu menatap patung St. Denis dengan rasa takjub, sekaligus ngeri—konon, kepala Santo itu terlepas karena hukum pancung, tapi magisnya, dia memegang kepalanya sendiri yang bau anyir darah. Saat itu, pada 04 September 2012, seorang santri “tradisional” telah menginjakkan kaki di sebuah kota yang punya sejarah panjang tetes darah di ujung bayonet: Paris.
Bagi lelaki yang lahir pada 14 Oktober 1985 itu, Paris adalah kota yang asing, juga tergesa-gesa: “Dari sebuah bangku di depan kafetaria, aku memandang dinding-dinding kampus yang tampak kusam di saat-saat cuaca mendung seperti ini. Namun denyut kehidupan tetap berjalan di dalamnya, dengan keriangan dan kehangatannya sendiri, juga kebekuan dan ketakacuhannya, seperti ritme kehidupan di Paris yang selalu sibuk dikejar dan mengejar waktu.”1 Muhammad Al-Fayyadl, yang akrab disapa Gus Fayyadl (selanjutnya ditulis GF), menuliskan itu pada pertengahan Oktober 2012 di sebuah kafetaria sembari memandang cat-cat kampus Paris VIII yang pucat—tapi bersejarah. Paris yang dingin itu punya sihir, tapi kata-kata tak cukup memadai menerjemahkan Paris yang sibuk: “Peristiwa-peristiwa berlalu-lalang dengan cepat di kota yang dingin ini, di mana cahaya matahari kadang tampak begitu kikir berbagi sedikit saja kehangatan cahayanya bagi kami, para penghuni kota ini. Di antara lalu-lalang peristiwa-peristiwa itu, yang tak semuanya tercatat atau teringat detail-detailnya—karena mereka sering kali berlalu lebih cepat daripada kata-kata—pada momen tertentu, pada titik tertentu dari gelombang kesadaranku, yang berusaha menandai, menamai, atau menorehkan seberkas saja makna pengalaman-pengalaman itu di dalam ingatanku…”2 Selain menjadi kota yang cukup pelik diungkap dengan kata-kata, Paris juga memaksa orang, termasuk GF, untuk tidak takabur. Sebuah kota yang memaksa kita untuk berkata, di kota ini “Aku hanya sesosok remeh.”
Di Paris, lelaki yang lahir di pesisir kota kecil di Jawa Timur, Paiton, Probolinggo itu, mau tak mau mengakui kesahihan puisi Rimbaud yang sering dibacakan Alan Badiou ketika mengajar mahasiswanya, termasuk GF, di Paris VIII: “Je suis un éphémere et point trop mécontent citoyen d’une métropole crue moderne parce que tout goût connu a été éludé” (Aku hanya sesosok remeh dan sama sekali bukan penduduk yang terlampau tak puas dari sebuah kota metropolitan modern yang kasar, karena semua aroma yang pernah dikenal telah lenyap…).”3 GF tak puas dengan kota itu—sama seperti Rimbaud terhadap London—justru karena ia merasa dirinya hanya sesosok remeh di tengah Paris yang penuh dengan pemikir gigantis. Di Paris, khas Parisien, GF menyadari satu hal: setiap orang hidup masing-masing; di Paris, ruang privat dijaga ketat. Konsekuensinya, masing-masing tak saling sapa—apa yang disebut Levinas, hilangnya transendentalitas Wajah Yang-Lain dan runtuhnya semesta ramah-tamah. Namun, tak semua. Kota itu masih menyisakan beberapa orang yang ramah dan sadar betapa hidup bukanlah tentang masing-masing, yang-satu; melainkan, hidup adalah perbedaan, bersama yang-lain. Hal itu tercermin, misalnya, di dalam diri filsuf-filsuf raksasa yang mengajar GF di Paris VIII. Mereka ramah, seakan-akan siap menyambut siapa saja yang (telah dan akan) datang.
Di November yang dingin di pinggiran Paris, setelah perjumpaan dan persinggungannya dengan filsuf raksasa, GF telah membangun “kota teks”nya sendiri. Beberapa nama yang tak lagi asing di telinga kita mulai memasuki gerbang “kota teks” GF itu: Alan Badiou, Rene Scherer, dan Helene Cixous. Cixous, filsuf perempuan, juga sastrawan yang menjadi nominasi Nobel Prize 2022 itu, punya kenangan tersendiri dengan GF. Kita tahu, Cixous adalah murid langsung Derrida; dan, Derrida, adalah hantu paling besar dalam karir filosofis seorang GF. Tak heran, laki-laki ugahari dan penuh tawadu’ itu terang-terangan berkata: “Bagiku dia adalah ‘Derrida’ dalam rupa feminin, mendengar kuliahnya mengingatkanku pada intonasi pemikir El-Biar itu…”4 Tahun pertama di Paris adalah masa di mana GF bertemu dan melihat langsung apa yang dulu hanya bisa ia lihat dan temui dalam huruf, dalam kata.
Pada 05 Maret 2013, di Paris yang menggigil, GF mendengar kabar yang menghentak: Hugo Chavez mangkat, rakyat Venezuela berkabung. Sang pelopor reformasi sosial (yang bernama Revolusi Bolivarian) itu mangkat; dan kabar meninggalnya terdengar jauh hingga di tengah salju Paris, GF menulis:
“Aku tak mengenal Chavez. Ia juga tak mengenal tingkah salju yang bersahabat di kota ini. Tak ada hubungan antara kami bertiga. Hanya, melihat grafiti-grafiti yang dicoretkan orang di dinding-dinding halte metro—pernah aku juga melihatnya sekilas kemarin di poster-poster iklan—semakin mafhum betapa kepergian orang ini mengagetkan banyak orang di kota ini; mereka yang bersimpati tentu saja pada perjuangan dan kegigihannya membangun sosialisme-demokratis di Venezuela. La lutte continue, pekik salah satu grafiti, “terus berjuang”. Yang lain: Chavez n’est pas mort, “Chavez belum mati”. Ini pasti kerjaan orang-orang gauchiste (kiri), atau anak-anak muda yang merasa Chavez bapak ideologis mereka.”5
Selama di Paris, GF tak hanya menikmati kota itu, melainkan bergerak dan aktif mengikuti isu-isu (juga diskursus [juga filsafat]) politik baik di Indonesia maupun di Prancis. Hal ini tampak, misalnya, dalam perjalanan GF di tengah salju lebat dari Paris ke Aachen, Jerman, bersama seorang eksil ’65 yang telah 30 tahun menetap, juga terlibat banyak di jaringan aktivisme, di Paris. Perbincangan tentang politik dan aktivisme ini mungkin cukup penting dalam karir aktivisme GF sepulangnya ke tanah air. Di Indonesia—seperti yang dikatakannya sendiri—GF berusaha untuk membangun gerakan “…dengan berangkat dari pergulatan konkret yang sedang mereka hadapi saat ini dan tradisi-tradisi revolusioner yang mereka miliki.”6 Adapun, tradisi revolusioner dan problem-problem sosial yang dimiliki oleh Indonesia, tak lain dan tak bukan, yang juga menjadi bagian penting dalam diri seorang GF, adalah umat Islam—khususnya pesantren.
Di Paris, GF juga cukup aktif mengikuti aktivisme; misalnya, ketika ia ikut solidaritas pembebasan bagi rakyat Palestina, juga beberapa pawai “politis” gerakan kiri, selama di Paris. GF bukanlah seorang pemikir yang hanya diam membatu di atas timbunan teks; GF adalah subjek yang aktif membela dan mendukung mereka yang—meminjam istilah Ranciere, filsuf yang juga GF tekuni selama di Paris—bagian yang bukan bagian. GF adalah seorang, meminjam julukan filsuf besar Alan Badiou, pemikir-pejuang. Tubuhnya tak bisa diam ketika ada rakyat yang tatal dan menangis saat rumah mereka dibuldozer oleh aparatus negara.
Dalam perbincangan pribadi dengan penulis, GF berkata dengan cukup lugas dan terang-terangan, tapi pada saat yang sama, anggun: “Ke Prancis saya sebenarnya mencari suaka sekaligus ‘tirakat pemikiran’ sampai semuanya terurai. Dan kebenaran yang lebih tinggi mencuat bak fajar pagi.”7 Benar, berpikir butuh keheningan dan kejernihan, kita butuh “suaka”, tempat pengasingan dari hiruk pikuk; lalu menemukan sebuah eureka—tentu, itu pedih. Namun, GF meneruskan, “Kepedihan kognitif belum ada artinya dibandingkan dengan kepedihan akibat tanahnya terampas.” GF semacam punya keyakinan subtil: pemikir tak bisa hanya duduk di atas sanggurdi teks; ia harus turun, memeluk tangis rakyat.
Namun, Paris hanyalah periode singkat; meskipun, sangat elementer terhadap perjalanan intelektual dan aktivisme seorang GF. Di Periode Paris ini, buku ketiganya—yang merupakan metamorfosa dari tesisnya di Paris VIII—terbit dalam bahasa Prancis: Fiction/Subjectivation Politique. Perjalanan GF pertama kali bermula dari pinggiran pesisir di desa kecil, Paiton; lalu melanjutkan nyantrik ke Sumenep; meneruskan jenjang sratata sarjana di Jogja; dan terbang menuju pusat Paris. Kuartet periodik ini, masing-masing mempunyai peran penting bagi seorang GF. Perjalanannya dimulai sebagai santri yang taat dan disiplin tinggi menimba ilmu (juga filsafat) agama; dan ini menjadi kondensasi bawah sadar terbesar seorang GF. Nyaris sepanjang karir intelektualnya, hingga sekarang, GF tak pernah terlepas dari isu-isu agama (baik dalam kerangka diskursus maupun aktivisme ‘politik’). Oleh karena itu, Periode Paiton dan Sumenep, sekitar taun 90an, adalah periode awal GF meniti karirnya sebagai penulis, pemikir dan pejuang. Sejak di Sumenep, lelaki serius tapi humoris dan penuh senyum itu, telah banyak menulis artikel (baik tulisan filsafat, sosial, agama maupun politik) di pelbagai media cetak; dan ia lebih menggila ketika di Periode Jogja.
Jogja adalah batu asah bagi ketajaman konseptual seorang GF—di periode ini, berangkali, GF sudah bisa diterawang jika kelak ia akan sangat rawan ditulis dalam buku sejarah. Di kota ini, GF menulis dua buku: Derrida (LKiS, 2005) dan Teologi Negatif Ibn ‘Arabi (LKiS, 2012). Selain itu, di Periode Jogja GF juga menerjemah beberapa buku, salah satunya, buku Suhrawardi, Hikmah Al Isyraq (Islamika, 2002). Selama Periode Jogja ini, GF menyusun dan mengembangkan berbagai proyek-proyek filosofis yang kelak akan diteruskan di Periode Paris. Pelbagai perjumpaan dan persinggungannya dengan beberapa pemikir Indonesia, seperti Sunardi dan beberapa sahabat intelektualnya baik di LKiS maupun di berbagai universitas—tak luput pula guru-guru spiritualnya—mempunyai sumbangsih yang cukup berharga dalam perjalanan seorang GF. Terdapat satu momen menarik yang patut ditandai di Periode Jogja ini, yakni ketika GF bertemu dengan filsuf besar perempuan sekaligus penerjemah De la Grammatologie karya masyhur Derrida: Gayatri Chakravorty Spivak. Konon, di bawah beringin legendaris di Universitas Sanata Darma itu, persisnya pada tahun 2006, Spivak memberi ceramahnya di langit Jogja yang terik. GF adalah salah satu audiens, dan bersama Sunardi, ia duduk berbincang dengan murid Derrida itu. Namun yang pasti, Periode Jogja adalah periode gila-gilaan seorang GF dalam mendaras timbunan konsep dan rimbunan teks.
Setelah Periode Paris, GF kembali ke muasalnya di pesisir. Dari pusat, ia kembali ke pinggir; dari akhir ia menuju awal: membersamai mereka yang butuh dan mengajar segudang teksnya yang tak tepermanai. Sesekali GF memberi berbagai ceramah publik di kota nostalgiknya, Jogja, dan di beberapa kota besar di Indonesia. Lelaki yang telah mencicipi banyak peristiwa itu, dari gigil salju hingga hujan tangis, saat ini ia kembali ke sebuah tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. GF hidup begitu zuhud dan takdzim, sehari-hari GF “…menyelam di Arab Klasik, membaca Al-Mubarrad, dll…selain bergumul dengan teks-teks yang sudah familiar, seperti Al-Ghazali, dll.”8 GF membaca, mengajar, dan menyusun manuskrip di tempat tinggalnya yang begitu teduh dan asri. Di dalam pesantren di ujung timur Probolinggo itu, kini ia melanjutkan—tepatnya mengatasi—hidup.
Sebagai mini biografis, tulisan ini sebatas representasi. Kita tahu, laiknya representasi, tidak ada yang murni representatif dalam menggambarkan dan memodelkan sesuatu. Tulisan ini sebatas menempatkan seorang GF dalam sebuah bingkai, dalam sebuah struktur yang dinamakan logika sejarah. Kita tahu, representasi tak selamanya menggambarkan apa yang hendak digambarkan, meminjam perkataan GF sendiri: “Sebuah biografi tak bisa meringkas hidup. Ia rekaman sebuah mozaik yang akan selalu bergerak dalam lipatan waktu.”9 GF belum selesai, dan sejarahnya masih terus bergerak. Kita tak pernah tau GF yang-akan-datang, tapi pada saat yang sama, kita harus menjemput GF yang-akan-datang itu. Kita tak perlu khawatir, GF selalu tau bagaimana cara menghadiahkan kita gelombang kejut.
Namun, setelah mini biografis ini ditulis, ada satu pertanyaan yang menyembul keluar—sebuah pertanyaan dari Derrida ketika diwawancarai oleh majalah LA Weekly, yang juga dikutip oleh GF di buku masa mudanya, Derrida—”Haruskah seorang filsuf menulis biografi?” []
Catatan Akhir
1 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (2), Monograf: 2012.
2 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (3), Monograf: 2012.
3 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (3), Monograf: 2012.
4 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (3), Monograf: 2012.
5 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (4), Monograf: 2012.
6 Muhammad Al-Fayyadl, Des Feuilles de Paris (4), Monograf: 2012.
7 Kutipan ini didasarkan pada percakapan pribadi secara tertulis dengan penulis.
8 Kutipan ini didasarkan pada percakapan pribadi secara tertulis dengan penulis.
9 Kutipan ini didasarkan pada percakapan pribadi secara tertulis dengan penulis